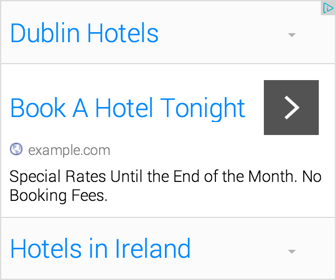SUARASMR.NEWS – Reformasi sedang disabotase dari dalam. Bukan dengan tank di jalanan, bukan dengan larangan berkumpul, melainkan melalui pasal, tafsir konstitusi, dan manuver elite di Senayan.
Yang lebih ironis, banyak tokoh yang dulu mengusung panji reformasi kini memilih diam bahkan berubah menjadi instrumen neo-Orde Baru yang dahulu mereka lawan.
Isu penghapusan pilkada langsung dan pengembaliannya ke DPRD adalah alarm paling nyaring dari kemunduran demokrasi itu.
Mari jujur pada sejarah. Pilkada langsung adalah salah satu kemenangan paling penting Reformasi 1998. Ia lahir dari rahim perlawanan terhadap sentralisme, oligarki, dan manipulasi kekuasaan ala Orde Baru.
Kini, di bawah rezim Prabowo, agenda itu hendak dikubur hidup-hidup dan dikembalikan ke status quo lama—dengan dalih rasionalitas anggaran dan tafsir konstitusi.
ARGUMEN BIAYA: DALIH ATAU MANIPULASI?: Dalih pertama yang terus digoreng adalah mahalnya biaya pilkada langsung. Mahar politik, politik uang, survei elektabilitas berbayar, hingga biaya pencoblosan disebut sebagai pemborosan APBN.
Fakta itu benar. Tapi sumber masalahnya sengaja dipelintir. Mahar politik bukan produk rakyat, melainkan keputusan partai politik sendiri. Jika partai mau, mahar bisa dihapus hari ini juga.
Politik uang bukan kesalahan demokrasi langsung, melainkan kegagalan partai menyiapkan kader yang berintegritas, berkapasitas, dan bermartabat. Ketika calon miskin gagasan dan karakter, uang menjadi satu-satunya senjata.
Survei elektabilitas mahal yang diwajibkan partai justru menyingkirkan calon berkualitas yang tidak bermodal. Ini seleksi berbasis uang, bukan kepemimpinan. Semua ini adalah dosa sistemik partai bukan alasan mencabut hak pilih rakyat.
Biaya teknis pilkada pun bukan masalah prinsip. E-voting adalah solusi nyata dan telah diterapkan di banyak negara. Infrastruktur Indonesia siap.
Bahkan dengan sistem manual pun, efisiensi bisa dilakukan lewat pengurangan TPS dan optimalisasi logistik. Kesimpulannya tegas: biaya bukan alasan sah untuk merampas kedaulatan rakyat.
KONSTITUSI DIJADIKAN TAMENG KEKUASAAN: Argumen kedua lebih berbahaya: mengatasnamakan konstitusi dan Pancasila. Sila keempat dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dipelintir untuk membenarkan pilkada lewat DPRD.

Ini tafsir sepihak: Permusyawaratan/perwakilan tidak pernah berarti mencabut hak elektoral rakyat. Hak memilih adalah hak personal warga negara, bukan mandat yang boleh diambil alih DPRD. Perwakilan bertugas memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan menggantikan suara rakyat.
“Dipilih secara demokratis” tidak identik dengan “dipilih oleh DPRD”. Demokrasi, secara etimologis dan substantif, adalah kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi langsung adalah bentuk paling murninya. Demokrasi perwakilan hanyalah kompromi pragmatis bukan superior secara moral.
Fakta paling telanjang: mayoritas rakyat menghendaki pilkada langsung. Yang mendorong pilkada tidak langsung hanyalah partai-partai politik. Di titik inilah parlemen gagal mewakili rakyat.
PETA GELAP SENAYAN: KEDAULATAN RAKYAT DI UJUNG TANDUK: Peta kekuatan di Senayan menunjukkan mayoritas DPR akan mendukung pilkada lewat DPRD. Artinya, kedaulatan rakyat akan dirampas secara konstitusional—persis seperti era Orde Baru.
Bergabungnya Partai Demokrat ke barisan ini menandai kekalahan hampir pasti rakyat. Isu barter kursi menteri mungkin ada, namun persoalannya lebih dalam: genealogi politik Orde Baru masih hidup.
Golkar sebagai pengusul utama adalah pilar Orde Baru. Gerindra, Demokrat, NasDem, Hanura—secara historis adalah metamorfosis dari induk yang sama. DNA politik mereka adalah DNA kekuasaan terpusat, bukan demokrasi partisipatoris.
Partai-partai Islam memilih pragmatisme, kehilangan figur visioner pasca Gus Dur. Suara reformis di dalam partai-partai itu tenggelam oleh arus besar oligarki.
PILIHAN TERAKHIR RAKYAT: Terlepas dari segala kritik terhadap PDIP, satu fakta tak terbantahkan: saat ini hanya PDIP yang berdiri di sisi rakyat dalam isu pilkada langsung.
Rakyat hanya punya dua pilihan:
● Pasrah, menyerahkan segalanya pada Senayan, dan menyaksikan kekalahan demokrasi.
● Atau berdiri di luar parlemen, seperti 1998, mendukung kekuatan yang masih melawan arus oligarki.
Seorang pengamat menyebut, 285 juta rakyat hari ini dijajah oleh 30 ribu elite oligarki politik dan kapital. Pernyataan ini pahit, tapi sulit dibantah.
Pertanyaannya sederhana: sampai kapan rakyat menerima keadaan ini sebagai takdir?
Bersuara dari luar Senayan bukan tindakan inkonstitusional. Justru itu intra-konstitusional namun ekstra-parlementer sah dan legitim, ketika parlemen tak lagi mencerminkan kehendak rakyat.
Di negara lain ada referendum. Di Indonesia, rakyat hanya punya suara jalanan dan solidaritas sipil. Jika tidak ingin kembali ke lorong gelap otoritarian Orde Baru, rakyat harus bersuara sekarang. Salam demokrasi dari Nian Tanah Sikka. (red/SHE)
Oleh: Dr. Ing. Ignas Iryanto SF, M.Eng.Sc, CSRS. Mantan Aktivis API Indonesia Berlin 1994–1998